Oleh: Anggita Dwi Febrianti
“Mati saja. Matikan aku, Ya Allah.”
Teriakan itu sudah menemaniku sejak 4 hari yang lalu. Tidak ada perbedaan dari 2 tahun sebelumnya selain rasa sakit yang memaksa tubuhnya untuk lebih bertahan. Kami hanya bisa menahan sesak sembari menulikan pendengaran di saat ibu kami menenangkannya perlahan-lahan.
“He e he e he e,” Gerutuannya kembali terdengar dan berangsur keras membungkam hujan.
“Sabar, Yah. Obat yang Ayah minum nggak bisa bekerja kalau Ayah teriak-teriak.”
“Sakit… sakit…sakit…kenapa nggak sembuh-sembuh?!”
Ibuku hanya diam sembari mengoleskan minyak kayu putih di perut dan punggungnya.
“Matikan aku, Ya Allah. Matikan aku.”
“Ayah nggak bisa mati. Ayah mau bawa apa buat hadapin Tuhan? Bekal Ayah udah banyak?”
“HWAAAH…matikan aku, Ya Allah!” Ayah memaksa tubuhnya berdiri dalam satu hitungan, “Antar aku ke Intan dan Asri. Kamu nggak sabar ngurus aku!”
Ibu membisu ketika nama itu kembali terucap dari bibir ayah. Walaupun ibu sudah menerima fakta bahwa mereka adalah keluarga di masa lalu, tetapi menyebut nama mereka di saat terendah bukanlah hal yang benar mengingat ada kami di sini. Ada kami yang mencoba kokoh untuknya. Ada kami sebagai keluarga miliknya. Ibu menarik napas sesak sembari meraih lengan ayah,
“Kalau nggak sabar, aku nggak mungkin disini, Mas”
“Pembohong. Arghhh sakit…minggir, nggak usah urus aku.”
Brakkk
Aku terlonjak mendengar suara itu. Aku bergegas ke kamar sebelah dan mendapati ibuku yang jatuh tersungkur menabrak lemari kayu.
“Pukul aku, Mas. Pukul! Aku udah sabar ngerawat, Mas. Mas yang nggak sabar cuma bikin aku capek. Nggak ada yang instan, semua butuh proses. Kalau nggak mau, Mas bisa pergi ke Asri”
Aku benci semuanya. Aku benci dengan kondisi yang membuat mereka dengan mudah untuk beralih. Tidak kah mereka berpikir untuk bertahan demi kami? Aku muak dengan ocehan yang selama ini aku dengar tapi aku tidak mampu melakukan apapun untuk itu. Aku muak.
“CUKUP! Kalau kalian pisah aku sama siapa, hah? Sama siapa? Aku nggak mau sendirian sama Adik.”
Mereka menatapku pias dengan air mata yang bergelinang. Mereka membisu setelah sadar bahwa apa yang terjadi mungkin menyakiti kami sebagai anak, Memaksa kami tumbuh tanpa figure ayah. Ibu membaringkan ayah ketika dahinya kembali mengerut menandakan sakitnya masih bersarang dalam perutnya. Ibu menghubungi keponakan ayah untuk membantunya pergi ke dokter dan meninggalkan kami yang masih menangis tersedu.
Keesokan harinya, aku ketahui bahwa ayah dan ibu akan pergi ke lab untuk merontgen perut ayah sesuai rujukan dari rumah sakit kemarin. Ibu mengganti baju ayah dengan yang baru, ibu membantu ayah untuk buang air kecil di tempatnya, Ibu membantu ayah untuk menyisir rambutnya dengan benar. Hati kecilku bersyukur melihat ayah yang sudah mampu buang air kecil dan penampilannya yang memukau.
Selepas kepergian mereka, aku memutuskan untuk membersihkan kamar ayah dengan adikku. Kami mengganti sprei dengan yang baru, menyediakan bantal tambahan, bahkan mengatur besarnya ventilasi dan sandaran yang biasa ayah gunakan.
“Mbak bersyukur, Dik. Ayah sudah bisa buang air kecil. Kalau begitu Ayah nggak apa-apa, kan, Dik?”
“Aku juga seneng, Mbak. Aku rasa ayah bakal sembuh lagi.”
“Nanti kamu bilangin Ayah buat nggak ngerokok lagi, ya, Dik. Supaya Ayah tetap sehat.”
“Kenapa bukan Mbak aja? Kalau sama aku, Ayah pasti nganggapnya nggak serius.”
“Gapapa, kamu aja, Dik. Ayah langusng nurut kok pasti.”
Ayah bersama ibu kembali dan mengatakan bahwa lab yang dikunjungi harus menggunakan sistem janji temu dan dokter di sana kebetulan hari Senin baru bisa. Seteleh menidurkan ayah kembali, aku dan ibu menjaganya di sampingnya. Ayah jauh lebih tenang dari kemarin, paling hanya mengerut sebentar dan tidak sampai berteriak. Aku berdoa dalam hati untuk kesembuhan ayah yang saat ini mencoba memejamkan mata. Sekarang pukul dua siang dan kami masih disampingnya. Adikku pun masih enggan untuk melihat ayah, mungkin kejadian kemarin masih menakutinya. Ayah mulai terbangun dengan hembusan napas yang halus. Mata teduhnya menyusuri bagian kiri dan kanan penglihatannya, dimana artinya menatap ibu kemudian aku. Mata itu memutar ke arah langit-langit dibarengi dengan tubuhnya yang sedikit terangkat hingga melahap napas ayah yang sedikit berderu. Saat itu, kenangan kami terhenti, mengacaukan ingatan dan menghancurkan hati kecil kami. Ibu menggoyangkan tubuh ayah kencang di saat kami masih mencerna apa yang terjadi. Kami kehilangan dia. Kehilangan segala tentangnya. Sekali lagi semestaku lenyap.
Aku masih menangis ketika mengingat momen itu bahkan hingga detik ini di depan pusara ayah. Aku menyesali gengsiku yang mengalahkan kepedulianku terhadapnya dan membuatku hanya terdiam ketika Ia menyakiti tubuhnya diam-diam lewat rokok itu. Aku menginginkan tanganku meraih tubhnya dalam dekapanku. Aku menginginkan kepalaku singgah di pangkuannya dengan hangat. Jika ada meraka yang mengadu pada ayahnya tentang keusilan temannya, aku pun ingin itu. Namun yang bisa kulakukan adalah mengelus pusaranya sembari mengatakan, “Ayah nggak usah khawatir. Ibu udah ngerawat aku dan Adik jadi orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayah percaya kan kalau aku mampu jadi rumah paling nyaman buat mereka bersandar? Ayah selalu ada dalam doa Natha, Kasya, dan Ibu. Istirahat yang tenang Ayah. Aku sayang Ayah”.
Ilustrator: Danendra






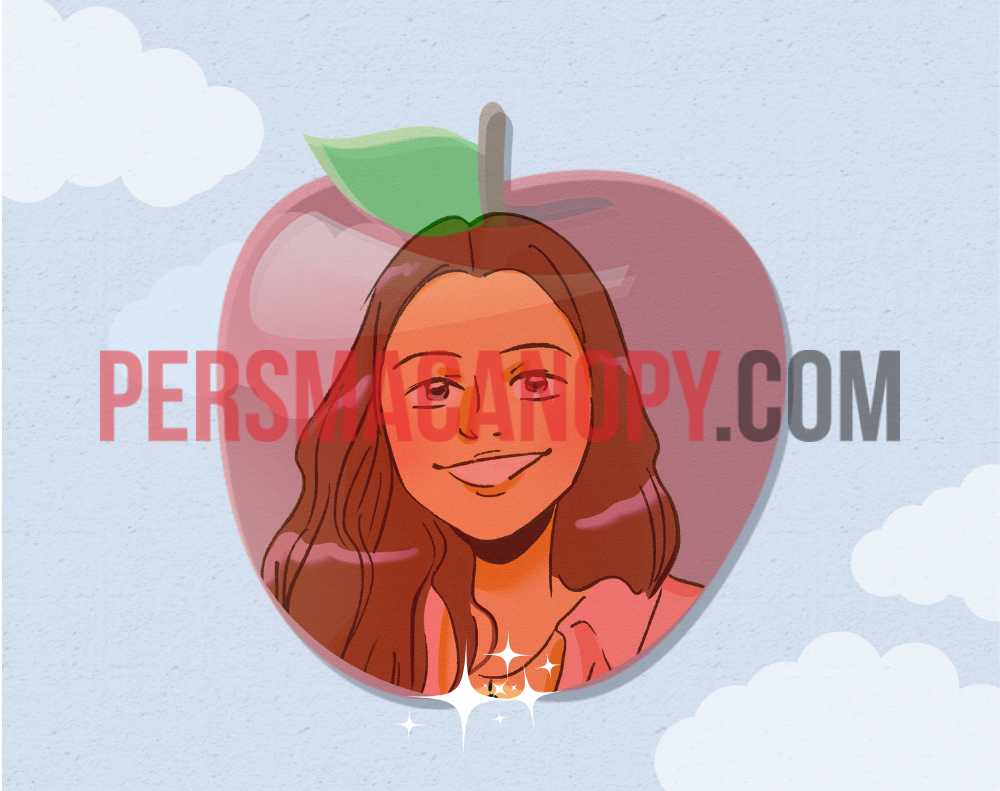








Leave a Reply